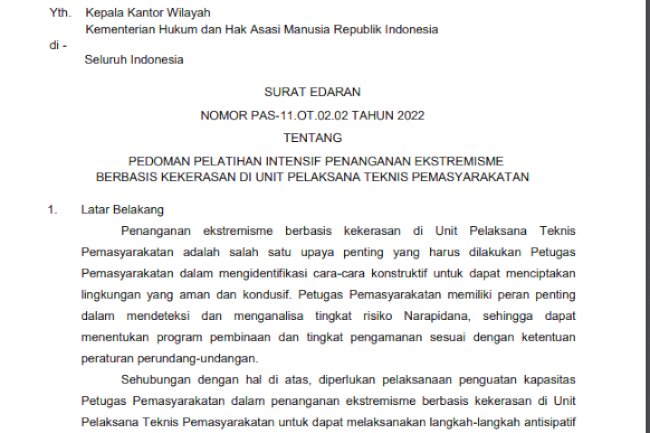Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis

Penjara atau sekarang disebut dengan istilah Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pelbagai macam orang dari pelbagai latar belakang pernah merasakan berada di balik jeruji besi. Dengan kerasnya kehidupan di penjara, banyak yang menyesali perbuatannya dan bertekad tidak mengulanginya lagi, namun tidak sedikit pula yang setelah bebas kembali masuk lagi dengan kasus yang sama atau bahkan dengan kasus lain.
Kenapa dan ada apa dengan penjara? Mengapa das sollen dan das sein-nya berbeda? Lembaga pemasyarakatan (lapas) yang diharapkan dapat mengubah WBP setelah bebas bisa menjadi orang yang lebih baik, namun nyatanya tidak sedikit yang kembali masuk dan menjadi residivis/bromocora. Lapas sering disebut sebagai sekolah kejahatan. Adapula yang menyebutnya miniatur kehidupan kriminal.
Masalah Pemenjaraan
Salah satu persoalan yang dihadapi pemenjaraan adalah perannya sebagai organisasi birokratis. Penjara tidak memiliki kemampuan memadai dalam menampung populasi tahanan dan narapidana sehingga tercipta kondisi overcrowded yang berimplikasi pada tidak terselenggaranya progran-program rehabilitasi dan reintegratif yang seharusnya dilakukan. Pada saat dicetuskannya Sistem Pemasyarakatan adalah asumsi bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan di penjara. Di dalam lapas, narapidana bisa mengikuti pembinaan dengan benar dan akhirnya bisa kembali ke masyarakat, namun narapidana yang mengikuti perilaku narapidana lain yang lebih kakap bisa semakin menjadi-jadi, bahkan profesional.
Pertanyaan yang muncul kemudian dalam perubahan ini apa perbedaan konsep Pemasyarakatan dengan pemenjaraan? Dalam sistem Pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana dinilai lebih manusiawi, tidak bersifat panitia, bersifat bukan pembalasan, dan perlakuan di dalam lapas adalah pembinaan yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat. Meskipun dalam rumusan tujuannya terdapat penekanan pada upaya pengembalian narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, namun tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan dalam diri dan perilaku narapidana (reformasi).
Menurut Teori Transmisi Kebudayaan sebagaimana dikutip Mukrima (1991) bahwa “dalam lingkungan sosial yang padat dengan kondisi kriminologi, bukan mustahil terjadi pewarisan nilai-nilai yang mendorong dilakukannya pelanggaran hukum.” Demikian halnya berdasarkan Teori Differential Association-nya Erwin H. Sutherland dan D. Cressey (Soekanto, 1997) bahwa “seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat.” Artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukan dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% adalah residivis. Khusus narapidana, sejumlah 204.185 adalah residivis. Ketika dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai asimilasi dan integrasi bagi narapidana sebanyak 30.000 lebih karena Virus Corona, masyarakat menjadi cemas ditambah berita tentang narapidana kembali melakukan tindakan kejahatan. Faktanya, angka residivisme di Indonesia masih dalam rentan rasio global, yakni 14-45%.
Masyarakat memang perlu waspada, namun perlu juga diketahui bahwa stigma negatif dan penyingkiran mantan narapidana dari kehidupan bermasyarakat justru malah memperburuk keadaan. Pemberian cap sebagai pelaku kejahatan dan mendapat penolakan dari masyarakat sebagai anggota masyarakat yang dapat dipercaya ketika seorang tersebut telah keluar dari lapas. Selain itu, narapidana yang bebas murni atau yang mendapat bimbingan dari balai pemasyarakatan kesulitan mendapat pekerjaan di luar lapas.
Hasil pembimbingan yang dilakukan petugas Pemasyarakatan yang bersifat bimbingan kemandirian hanya sebagai bekal mencari pekerjaan dan untuk bisa menyalurkannya pihak lapas sendiri belum bisa melakukannya sehingga mantan narapidana harus mencari pekerjaan sendiri. Ini menjadi dilema bagi mantan narapidana karena di satu sisi keberadaan mereka masih dianggap jahat di tengah-tengah masyarakat, di sisi lain narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus, namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja atau pemberian modal sehingga mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya. Padahal satu-satunya peluang bagi mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri mantan narapidana muncul persepsi dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas, yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.
Dampak seperti stigmatisasi masyarakat terhadap seorang mantan narapidana menjadi penyebab utama terjadinya residivis. Pihak lapas sudah bekerja maksimal untuk melakukan pelbagai pembinaan keterampilan sehingga lingkungan masyarakatlah yang akan menjadi tumpuan terakhir seorang mantan narapidana. Apabila masyarakat bisa menerima kembali seorang mantan narapidana, tentu saja akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang mereka dapatkan di dalam lapas dengan mendapatkan pekerjaan.
Sebaliknya, jika terjadi penolakan keras, tentu akan berdampak negatif kepada seorang mantan narapidana karena mereka tidak diberikan ruang untuk kembali menjalankan fungsi sosial seperti masyarakat lainnya sehingga akan menimbulkan frustasi bagi mantan narapidana akibat pengucilan tersebut. Tentu saja kondisi itu sangat potensial membuat seorang mantan narapidana mengulangi kejahatannya sebagai jalan terakhir untuk tetap melanjutkan hidupnya.
Penulis: Ahmad Arif (Lapas Perempuan Sungguminasa)
What's Your Reaction?